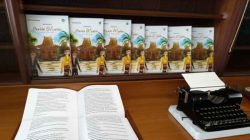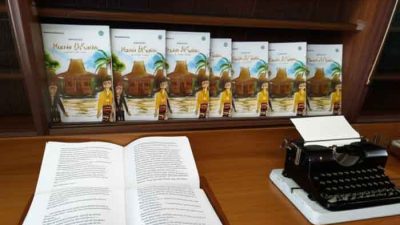Begitu berpapasan, si penumpang menyuruh kusir berhenti. Penumpang yang ternyata bangsawan itu lalu menghampiri lelaki tua. Dia bertanya mengapa tidak menunduk? Lelaki tua itu pun bilang dia tidak tahu siapa yang dihadapinya. Lelaki tua itu dicambuk bangsawan hingga tersungkut ke tanah. Mulutnya berdarah. Setelah bangsawan pergi, dia bangkit dan meneruskan pulang ke rumahnya.
Begitu berpapasan, si penumpang menyuruh kusir berhenti. Penumpang yang ternyata bangsawan itu lalu menghampiri lelaki tua. Dia bertanya mengapa tidak menunduk? Lelaki tua itu pun bilang dia tidak tahu siapa yang dihadapinya. Lelaki tua itu dicambuk bangsawan hingga tersungkut ke tanah. Mulutnya berdarah. Setelah bangsawan pergi, dia bangkit dan meneruskan pulang ke rumahnya.
Tiga hari kemudian, bangsawan itu datang dengan kusirnya yang diantar oleh kakaknya. Mereka minta maaf karena telah memperlakukan lelaki tua itu dengan semena-mena. Pasalnya, si bangsawan tidak dapat bicara. Selanjutnya, dia pun disembuhkan oleh lelaki tua itu, yang selanjutnya si bangsawan ingin belajar mengaji di pesantren dan di langgar si lelaki tua tersebut.
Identitasnya terletak pada kebiasaan yang ditampilkan tokoh dalam cerpen, misalnya sehabis subuh tokoh itu wiridan. Kendaraan yang ada, dokar, dan pakaian yang dikenakan si tokoh, yang merupakan manifestasi dari judul dan sebentuk simbol. “Dia mempercepat jalannya sekarang. Sarungnya yang putih berkotak-kotak hitam tipis, baju lengan panjangnya yang juga putih dan serbannya yang putih berkibar-kibar oleh angin. Seperti seekor burung putih, ia meluncur cepat di tanah yang datar itu.”
Selain itu, latar dan penyebutan tempat oleh tokoh menunjukkan kekhasan lokal, seperti adanya beberapa tempat di Madura: Pesantren Guluk-Guluk, Pasar Seronggi. Hal Iainnya adalah berbicara dengan alam, yang lazim dalam khasanah sufi atau wali di Jawa, terutama Jawa Timur, yang dikenal dengan wali lima-nya.
Cerita “Burung Putih” tersebut seakan-akan berparalel dengan “Kera Bisa Mengaji”, sebuah puisi yang ditulis oleh Lukman Hakim A.G. yang dimuat Radar Madura, yang akan dikupas dalam subbab Leluhur. Jika berkaca dari hal itu, tidak heran, apabila aku lirik dalam puisi “Panoteng Madura”, merasa teraniaya dengan stigma negatif yang kerap terlontar pada etnisnya, seperti angkuh, carok dan kekerasan. Aku merasa teriris, sedih dan syahdu sehingga aku lirik pun menyatakan bahwa apa yang terjadi itu sebenarnya adalah pandangan orang luar, pandangan pihak yang tidak mengerti kompleksitas hidup dan kultur. Simbol sabit dia jadikan satu penanda kultur yang tidak selalu terkait dengan darah. Untuk balas dendam, atau untuk kekerasan. Namun, sabit sangat simbolik.
Tajamnya yang ke dalam adalah kepekaan diri, sedangkan keras/tumpul di luar adalah keras menghadapi dunia. Masalah keras menghadapi dunia karena alam Madura memang keras. Tegalan dan alam keras telah menyumbangkan identitas khusus pada orang Madura, seperti yang diungkapkan oleh Kuntowijoyo dan Subaharianto (2004:13—49). Menurut mereka, tandus dan gersang melahirkan tradisi merantau orang Madura, sedangkan ekosistem tegal membentuk identitas Madura. Sementara itu, bentuk sabit yang melengkung atau tunduk merupakan bukti orang Madura itu patuh kepada ‘pucuk’ tertinggi.
Ihwal mengungkap Sisi Iain dari Madura terdapat pula dalam puisi Abdul Jalal, yang terhimpun dalam kumpulan puisi Madura Nemor Kara (Kemarau Panjang), (2006). Puisi tersebut memuat data etnografis Madura. Di bait pertama terdapat ungkapan ‘menanam tembakau’. Seperti diketahui, Madura identik dengan tembakaunya yang baik. Selanjutnya parebasan Madura, ‘berbantal ombak berselimutkan angin’ juga dijadikan sandaran puitik. Bait kedua berisi data etnografis dan geografis, misalnya dikelilingi Laut Jawa, karapan sapi, dan ada ungkapan sopan santun.
Kondisi ini seakan-akan berusaha mendobrak stigma bahwa orang Madura itu tidak kenal santun dan penuh kekerasan. Pada bait selanjutnya, aku liris mengaku bahwa di madura terdapat orang sakti dan mulia (dalam hal ini sebenarnya masuk dalam kapasitas identitas yang menjunjung tinggi leluhur. Selain itu, aku liris mengaku Madura sebagai tanah luhur dan tumpah darah, yang mungkin menurut Hariyadi (1981), dianggap kurang nasionalis dan mengindonesia. Namun, apa yang diungkapkan adalah sesuatu yang niscaya, ketika konstruksi Indonesia sering dipahami sebagai sebuah ‘komunitas terbayang’, yang riil adalah kondisi etnik yang pada akhirnya menyusun keindonesiaan. Hal itu diakui sendiri oleh Abdul Jalal. Disebutkan bahwa orang Madura tersebar ke antero Nusantara sebagai pemerkaya multikultur bangsa. Verbalitas yang diusung puisi itu pun berlangsung sampai bait keempat, yang merupakan bait terakhir. Berikut ini kutipan bait pertama:
Ajhemmor ѐ tengnga amparan bhumi sѐ luwas
Namen bhãko dhãddhi sa alas
Kapanasan, kacelepan, dhãddhi pangodi’na rѐ sa’arѐ
Abhãntal ‘sapo’ angѐin salanjhãngnga
(Nemor Kara, 4)
Terjemahan:
Berjemur di tengah hamparan bumi luas
Menanam tembakau menjadi sealas
Kepanasan, kedinginan, menjadi kehidupan setiap hari
Berbantal ombak berselimutkan angin selamanya
Lukman Hakim A.G., penyair muda Madura, juga berusaha membaca Madura dengan cara yang berbeda. Puisinya yang berjudul “Madura” sepintas hampir senapas dengan puisi Abdul Jalal, sebuah usaha membaca Madura dari dalam dan mengabarkannya ke luar untuk melawan stigma yang terlanjur dipercaya. Dalam “Ghendhing Madura”, Lukman Hakim A.G., juga berbicara tentang Madura, tetapi dari seni keseniannya, termasuk tradisi rokat dengan membaca macapat yang diiringi suara kendang dan trompet, yang biasa disebut musik soronen. Puisi itu seakan mendedahkan pada pembaca, bahwa di balik riuh kendang dan terompet, terdapat makna tertinggi yang bisa digapai, terutama dalam masyarakat Madura. Apalagi tradisi mamaca, yaitu membaca macapat di masyarakat masih ada meski sudah langka diperhatikan. Namun, di balik pembacaan itu, ada ikhwal yang ingin direnda. Dalam satu sisi, hal itu terkait dengan masalah mistifikasi dari kesenian tradisional yang mengarahkan para pelaku dan pendengar untuk memperoleh beragam manfaat secara praktis dan idealis: ‘menenangkan hati, menjernihkan pikiran, rasa khawatir tidak berserakan’. Perhatikan kutipan berikut.
Bãkto samangkѐn
Saronѐn ghendhing orѐng sobung sѐ open
Ta’ ekaeding ranying, maskѐ
Coma aella’ tabing cѐng nyeccѐng
Nang nѐѐѐng niiing ghung
Patennang atѐ, pabhenning pekkѐr
Rassa kobãtѐr jhã’car-kalacѐr
Ngireѐng panyettong.
Ma’ ontong ta’ rѐkong dalem arong-rong kamarong
Eko’ongnga lorong.
(Nemor Kara, 9)
Terjemahan:
Waktu sekarang
Tak banyak yang menaruh hati pada gending soronen
Tidak didengar nyaring, meski
hanya berjarak gedek
(Nang ning nong ng neng gung) menenangkan hati, menjernihkan pikiran rasa khawatir tidak berserakan mari menyatu. Supaya beruntung tidak repot dalam meratapi keadaan di tepian jalan
(Nang ning nong ng neng gung) menenangkan hati, menjernihkan pikiran rasa khawatir tidak berserakan mari menyatu. Supaya beruntung tidak repot dalam meratapi keadaan di tepian jalan