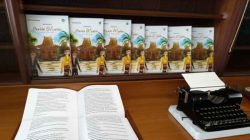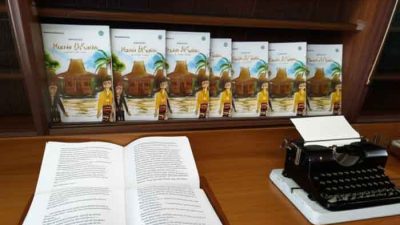Dari beberapa karya yang berhasil dihimpun dalam rentang waktu lima tahun, mulai 2005— 2009, spirit Maduranya masih kental. Meskipun demikian, asumsi awal penelitian ini adalah bahwa dalam dalam karya itu terdapat ikhtiar pembacaan kembali pada identitas dan warna lokal Madura. Hal itu seiring dengan laju zaman serta pengaruh global yang sedang bergelayut di setiap segmen kehidupan masyarakat. Ihwal tentang perubahan dan pergeseran itu sangat mungkin terjadi mengingat pada rentang 2005—2009 merupakan rentang waktu yang cukup berarti bagi pengaruh luar terhadap generasi penulis Madura mutakhir, di antaranya adalah terbukanya akses informasi dan keberadaan Jembatan Suramadu. Sementara itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kebudayaan.
Dari beberapa karya yang berhasil dihimpun dalam rentang waktu lima tahun, mulai 2005— 2009, spirit Maduranya masih kental. Meskipun demikian, asumsi awal penelitian ini adalah bahwa dalam dalam karya itu terdapat ikhtiar pembacaan kembali pada identitas dan warna lokal Madura. Hal itu seiring dengan laju zaman serta pengaruh global yang sedang bergelayut di setiap segmen kehidupan masyarakat. Ihwal tentang perubahan dan pergeseran itu sangat mungkin terjadi mengingat pada rentang 2005—2009 merupakan rentang waktu yang cukup berarti bagi pengaruh luar terhadap generasi penulis Madura mutakhir, di antaranya adalah terbukanya akses informasi dan keberadaan Jembatan Suramadu. Sementara itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kebudayaan.
Studi Kebudayaan (Cultural Studies)
Sebagai produk budaya, sastra juga integral dengan unsur budaya lainnya untuk bermain dalam ruang kebudayaan secara menyeluruh. Melalui sastra, dapat ditemukan keberadaan, kesadaran dan warna masyarakat yang menjadi latarnya. Kajian budaya memberikan ruang yang cukup luas untuk mendialogkan berbagai produk budaya, mulai dari sastra dengan politik, sosial, budaya dan bidang lainnya. Dari pertemuan dengan berbagai produk budaya itu, peran sastra dapat menjadi signifikan dalam kerangka kebudayaan, juga dapat terlihat kekuatan sastra dengan metateksnya dalam memengaruhi dan mewakili budaya masyarakatnya.
Ihwal cultural studies, Baker (2004:32) menjelaskan bahwa meskipun karya tekstual tampil dengan banyak sampul, termasuk kritik sastra, tetapi tiga cara analisis yang cukup terkemuka dalam cultural studies adalah semiotika, teori narasi dan dekonstruksionisme. Semiotika mengeksplorasi bagaimana makna yang terbangun oleh teks telah diperoleh melalui penataan tanda dengan cara tertentu dan melalui kode budaya. Analisis itu banyak mengambil data dari ideologi dan mitos teks. Kedua, teks sebagai narasi. Teks mengisahkan cerita, baik itu tentang teori relativitas Eisntein, teori identitas Hall maupun serial dalam televisi/pertunjukan teater. Konsekuensinya adalah bahwa teori narasi memankan suatu peran dalam cultural studies. Narasi adalah penjelasan yang tertata urut yang mengklaim sebagai rekaman peristiwa. Narasi merupakan bentuk terstruktur, yaitu kisah membuat penjelasan tentang bagaimana dunia ini. Narasi menawarkan kerangka kerja pemahaman dan aturan acuan tentang bagaimana tatanan sosial dikonstruksi dan dalam melakukan hal itu narasi menyuplai jawaban atas pertanyaan: bagaimana seharusnya kita hidup. Hal ketiga yang menjadi pisau analisis dalam cultural studies adalah dekonstruksionisme. Baker (2004:33) menjelaskan bahwa mendekonstruksi berarti ambil bagian, melucuti untuk menemukan dan menampilkan asumsi teks.
Di Sisi Iain, dalam penelitian ini, teori identitas menempati posisi urgen ka rena ideologi yang diusung dalam penelitian ini adalah menelusuri identitas yang mengarah pada semangat ‘post tradisi’. Perihal identitas, Cavallaro (2004:131) mengungkapkan bahwa manusia dan lingkungannya memperoleh makna dari keterpautannya dengan konstruksi-konstruksi simbolik. Diandaikan bahwa elemen fisik, psikologis, politis, ideologis, seksual dan rasial memainkan sebuah peran kunci dalam konstuksi identitas. Identitas dalam pandangan Barker (2004: 170) sepenuhnya merupakan konstruksi sosial dan tidak mungkin ‘eksis’ di luar representasi budaya dan akulturalisasi.
Bakerjuga telah menegaskan bahwa identitas merupakan ‘seluruh aspek’ budaya yang spesifik menurut ruang dan waktu tertentu. Hal itu berarti bentuk identitas dapat berubah dan terkait dengan berbagai konteks sosial dan budaya. Gagasan bahwa identitas bersifat plastis dipertegas oleh argumen yang disebut antiesensialisme strategis. Menurut versi itu, kata tidak dipandang memiliki acuan dengan aspek esensial atau universal karena bahasa ‘mencipta’ daripada ‘menemukan’. Dengan demikian, identitas adalah konstruksi diskursif yang berubah maknanya menurut ruang, waktu dan pemakaian (Barker, 2004: 170-1).
Sementara itu, dalam pandangan Wardi (Muji Sutrisno, 2007:115) dalam dunia kontemporer seperti sekarang ini telah terjadi ‘krisis’ identitas dan subjektivitas. Sebagai tandanya, munculnya begitu banyak proses pencarian identitas. Krisis dimaksudkan sebagai suatu kondisi, identitas dan subjektivitas yang ada sekarang sejak lahir digugat. Dengan kata Iain, ide identitas dan subyektivitas sebagai suatu ‘esensi’ tetap dan juga ide identitas dan subjektivitas sebagai suatu gen biologis dipersoalkan. Krisis terjadi menurut Woordward (via Wardi, 2007) karena dua hal. Pertama, karena adanya perkembangan teknologi zaman modern; kedua, karena meningkatnya arus globalisasi, termasuk di dalamnya juga terkait dengan migrasi atau perpindahan penduduk.
Untuk mengatasi krisis, perlu mendefinisi ulang ide/konsep identitas. Dalam ranah kajian budaya, pada akhirnya identitas dipahami sebagai suatu ‘entitas yang dapat diubah-ubah menurut sejarah, waktu dan ruang tertentu. Tidak ada ‘yang tetap (esensi) dalam entitas tersebut, semuanya dapat ‘dibuat’ dan ‘dibuat lagi’. Identitas juga dipahami sebagai sebuah proyek diri. Dalam hal itu, Wardi mengacu pada pandangan Giddens yang memandang bahwa identitas tercipta karena adanya kemampuan untuk mempertahankan narasi diri. Di dalam narasi diri, yang dituntut adalah kemampuan untuk membangun perasaan yang konsisten soal kesinambungan biografi diri (Sutrisno, 2007: 118). Dari konsepsi itu, akhirnya muncul keterpecahan identitas (yang merupakan usaha membaca identitas secara Cartesian ke identitas terfragmentasi model postmodern) dan politik identitas yang mengacu pada wacana bahasa.
Karya Sastra Regionalisme dan Warna Lokal
Dalam kesempatan menyangkut warna lokal dan regionalisme, akan dibungkus dengan jargon lokalitas. Untuk yang terakhir biasanya diperlawankan dengan sastra nasional, tetapi dalam konteks itu, kaidah sastra regional digunakan sebagai sarana untuk memperkukuh paradigma lokalitas. Ratna (2005:389) membedakan antara sastra warna lokal dan regionalisme. Menurutnya, karya sastra warna lokal adalah karya yang melukiskan Ciri khas suatu wilayah tertentu ditandai dengan pemanfaatan latar. Adapun sastra regionalisme didasarkan pemahaman lebih mendalam mengenai kehidupan manusianya yang bertujuan menverifikasi pola perilaku dan kebudayaannya.
Ditegaskan bahwa sebagai aliran realisme warna lokal hanya menyajikan permukaan lokasi tertentu. Caranya dengan melukiskan unsur yang tampak, sebagai dekorasi tanpa menyelami kehidupan yang sesungguhnya. Unsur yang dimaksud adalah pakaian, upacara, kebiasaan sehari-hari, perangai dan topografi. Sastra regionalisme pada dasarnya juga melukiskan keadaan geografis, latar, adat, tradisi atau kebiasaan dan sebagainya. Perbedaaannya adalah bahwa sastra regionalisme memberi perhatian pada misi dan memiliki visi/tendensi yang lebih sublim karena arah yang dituju adalah penampilan adanya kekhasan regional tersebut. Ratna memberi contoh bahwa yang dimaksud dengan sastra regional di Indonesia adalah sastra yang menggunakan bahasa daerah. Tak heran, jika sastra regional diperlawankan dengan sastra nasional. (Ratna, 2005:390-1). Dari pemerian tersebut sebenarnya akar warna lokal dan regional sama, tetapi keduanya berakar dari tradisi keilmuan yang berbeda. Keduanya berbicara soal lokalitas, yang digagas bukan hanya soal permukaan, melainkan kekhasan yang bersifat mentalitas yang mendasari apa yang tampak dan terjadi di permukaan.
Ratna (2005:395) mencatat bahwa dalam sejarah sastra Indonesia yang dikenal adalah sastra warna lokal, yaitu karya sastra dengan melukiskan ciri daerah tertentu. Menurutnya, warna lokal memang tidak hanya melulu pedesaan tetapi, juga perkotaan. Warna lokal dalam sastra sangat relevan dengan bigkai kebangsaan Indonesia yang bersifat multikultur dan memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Beberapa ahli mencatat beberapa sastra warna lokal yang terkait dengan agama, kepercayaan, kehidupan kelompok atau suku, sistem pertanian, kekerabatan, mitologi, takhayul dan lainnya (Ratna, 2005: 395).
Jika dilihat sekilas, pemerian terminologi tersebut mirip dengan sastra regional. Oleh karena itu, kedua terma itu dalam penelitian ini akan digunakan senyampang memberi satu acuan perihal lokalitas yang hendak didesakkan, karena lokalitas yang dimaksudkan dalam hal itu terkait dengan warna lokal dan regional (alpa bahasa daerah, tetapi memiliki spirit atau kekhasan daerah). Apalagi, Ratna (2005:396) lebih lanjut menjajarkan antara sastra warna lokal, sastra pedesaan dan sastra regionalisme dengan mengatakan: “penulisan sastra warna lokal, sastra pedesaan, dan sastra regionalisme pada dasarnya lebih sulit dibandingkan dengan genre sastra yang lain.”
Sebagai bukti adanya epistemologi yang sama di antara regionalisme dan warna lokal adalah adanya pengertian lain dari warna lokal yang tidak sekadar permukaan. Ratna (2005:397) menegaskan: ‘sebagai dokumen, sastra warna lokal dan dengan demikian juga karya sastra pada umumnya berfungsi untuk memperkenalkan tema, pandangan dunia, kecenderungan masyarakat kontemporer, aliran, paham dan ideologi dominan dalam suatu kolektivitas’. Bandingkan dengan kaidah Holman (Ratna, 2007) menyebutkan bahwa dalam sastra regionalisme personalitas tokoh merupakan representasi geografis. Biasanya hal itu menggunakan cara: (1) melukiskan ciri khas lokasi tertentu dengan cara menampilkan detail kehidupan masyarakatnya; (2) melukiskan ciri khas melalui sudut pandang tertentu, misalnya dengan melukiskan kehidupan agraris sebagai reaksi terhadap industrialisme.