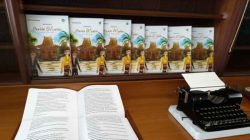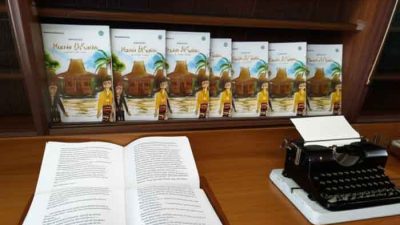Mamaca: Sastra Lisan Masyarakat Madura
Oleh: Panakajaya Hidayatullah
Ketika kita membicarakan tentang kesenian tradisi, hal yang tak pernah luput dari pembahasannya ialah stereotip tentangnya. Sedere-tan stereotip tersebut memandang seni tradisi sebagai sesuatu yang ketiggalan zaman, kuno, primitif, eksotik dan mungkin sebagian orang menganggapnya kurang bisa berkembang.
Namun sebenarnya seni tradisi selalu menyimpan kreativitas, intelektualitas, dan daya estetik yang tinggi, yang sebenarnya merupakan kekayaan intelektual masyarakat, khususnya dalam konteks budaya lokal. Kekayaan intelektualitas tersebut dapat kita lihat melalui salah satu kesenian yang bersumber dari sastra lisan masyarakat Madura.
Masyarakat Madura mewarisi tradisi sastra lisan yang sampai saat ini masih dipertahankan, yakni tradisi mamaca. Mamaca adalah salah satu seni tradisi yang hidup dalam masyarakat Madura sejak lama, kemungkinan sejak masuknya Islam ke Jawa dan Madura. Istilah mamaca berasal dari bahasa Madura yang memiliki arti ‘membaca’ dan memiliki kedekatan makna dengan istilah macapat di Jawa.
Mamaca merupakan sebuah kegiatan membaca teks berupa puisi atau cerita dengan cara dilagukan/dinyanyikan dalam bentuk tembang (tembhâng), dan dijelaskan/diinterpretasi (tegghes) dalam bahasa Madura. Teks yang diba-cakan ditulis dengan menggunakan huruf Arab-Melayu, ada juga yang menggunakan huruf Arab Pegon dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo.
Dalam tradisi mamaca terdapat dua peran pelaku seni, yaitu tukang baca (tokang maca/pamaos) dan juru ulas (tokang tegghes/paneg-ghes/pamaksod). Tukang baca memiliki peran membaca teks cerita dengan cara menyanyikannya dalam bentuk tembang dari bait per bait. Kemudian dilanjutkan oleh juru ulas yang berperan menerangkan secara langsung apa yang baru saja ditembangkan oleh tukang baca.
Teks mamaca ada beragam jenisnya di antaranya yaitu Nor Bhuwwât yang berisi kisah Kanjeng Nabi Muhammad, Pandhâbâ berisi kumpulan cerita Pandawa, dan Ju-wâr Manik. Teks tersebut memiliki fungsi dan pemaknaannya sendiri. Biasanya pemilihan teks yang di-bacakan menyesuaikan dengan konteks acaranya.
Di Situbondo dan Bondowoso, mamaca biasa digunakan dalam dua jenis acara yakni acara yang bersifat sakral seperti Rokat Pandhâbâ (ruwat anak pandawa), Mèrèt Kandung (selamatan kehamilan), Molotan (peringatan maulud Nabi) dan Isra’ Mi’raj (peringatan Isra’ Mi’raj); serta acara yang bersifat hiburan atau tak resmi yaitu kompolan mamaca (per-kumpulan mamaca), arisan mamaca (arisan mamaca), dan pertunjukan.
Teks Pandhâba dibacakan hanya khusus untuk acara meruwat anak, Nor Bhuwwât dibacakan untuk Mèrèt Kandung, Molotan, dan peringatan Isra’ Mi’raj, sedangkan untuk acara hiburan umumnya membacakan teks cerita Juwâr Manik. Selain untuk konteks acara di atas, teks Nor Bhu-wwât juga umum dipakai untuk oghem (meramal). Sebagian orang Madura masih percaya bahwa teks Nor Bhuwwât memiliki nilai magis dan dipercaya mampu membaca nasib dan karakter diri seseorang. Menurut penuturan pelaku, oghem merupakan pembacaan atas dirinya sendiri (maca abâ’na dhibi’).
Seni Pertunjukan Mamaca
Mamaca pada dasarnya merupakan seni tradisi yang menonjolkan aspek suara (vokal). Pertunjukan mamaca tidak menggunakan unsur visual apapun, tidak ada penyutradaraan tubuh, tidak ada gerak, dekorasi, panggung, ataupun aksesoris lainnya. Karena ketiadaan unsur yang bisa ditonton maka semua tergantung pada kekuatan imajinasi yang diaktualisasikan oleh gaya tutur kedua peran pelakunya yaitu tokang maca dan juru ulas.
Teknik vokal yang tinggi merupakan turunan dari teknik dhâlâng, baik dhâlâng pewayangan ataupun dhâlâng topeng. Mereka mampu menghidupkan kata, dialog dan deskripsi dalam bentuk estetik. Suara berkarakter teater itulah kekuatan dari seni tradisi mamaca, dan sebenarnya bisa dikatakan sebagai bentuk seni pertunjukan yang tidak visual.
Bentuk pertunjukan mamaca ada bermacam macam. Bouvier membagi repertoar mamaca menjadi tiga yaitu repertoar naratif yang terdiri dari carèta; repertoar prosodis yang terdiri dari tembhâng; dan repertoar musikal yang terdiri dari ghendh-ing. Penyajian ketiga bentuk tersebut sebenarnya bergantung pada selera dan kekuatan ekonomi si penanggap atau pemilik hajat.
Bentuk yang paling sederhana ialah melakukan mamaca tanpa iringan musik instrumental, artinya hanya ada peran tokang maca dan juru ulas. Paling sedikit dilakukan oleh 2-6 orang, 1 orang sebagai juru ulas, dan sisanya bergantian men-embangkan teks. Beberapa jenis tembang yang dijadikan pedoman dalam melagukan teks mamaca Madura adalah tembhâng Kasmaran,
Sènom, Salangèt, Pangkor, Artatè dan Pucung. Bentuk yang lainnya ialah menambahkan instrumen suling bambu dalam pertunjukan. Instrumen suling dimainkan untuk memperindah melodi vokal si penembang (tokang maca) dengan memainkan nada-nada yang tumpang tindih. Bentuk yang paling lengkap dalam pertunjukan mamaca dikenal dengan istilah ghendhirân, yaitu menembangkan teks mamaca dengan iringan musik ghendhing dari beberapa instrumen gamelan Madura (klènèngan) dan tari-tarian (tanda’)
Syiar Islam Lewat Mamaca
Menurut beberapa pelaku mamaca di Situbondo, mamaca merupakan kesenian yang lahir dari proses akluturasi budaya Jawa, Arab dan Madura. Mereka meyakini bahwa mamaca merupakan warisan dari para Wali Sanga. Teks mamaca digunakan untuk syiar Islam di tanah Jawa dan Madura. Kedatangan Wali Sanga dengan ajaran Islam tidak serta merta mengubah tatanan nilai dan budaya masyarakat Jawa seluruhnya. Mereka melakukan syiar islam dengan cara-cara kultural. Nilai-nilai Islam diinter-nalisasi ke dalam budaya lokal, tanpa menghilangkan esensi utamanya.
Melalui budaya-budaya lokal, nilai-nilai Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat, Simbol-simbol yang digunakan oleh Wali Sanga adalah simbol-simbol lokal yang sudah menjadi bagian dari masyarakat setempat. Simbol tersebut kemudian dihubungkan dengan simbol-simbol Islam.
Sebelum datangnya Wali Sanga, masyarakat Jawa dan Madura telah mengenal cerita Mahabarata, bahkan kisah tersebut dijadikan sebagai pedoman hidup mereka. Wali Sanga kemudian menginternalisasi nilai-nilai dan akidah ke-Islam-an ke dalam narasi cerita Mahabarata (pandhâbâ) tersebut. Kisah pandawa lima yang tadinya bernuansa Hindu kemudian menjadi kisah pandawa lima yang bernafas Islam.
Dalam kisah pandhâ-ba, teks mamaca pandawa lima selalu dihubungkan dengan rukun Islam yang juga berjumlah lima. Begitupun juga dengan tokoh Betarakala yang tidak diasosiasikan sebagai makhluk gaib namun dihubungkan dengan sifat-sifat amarah yang dimiliki oleh setiap umat manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Quran. Melalui teks narasi pandawa lima-lah, Wali Sanga mengembangkan nilai-nilai pendidikan Islam.
Budaya Arab yang dibawa oleh para Wali Sanga tersebut juga turut mewarnai pembentukan kebudayaan di Jawa dan Madura. Dalam teks mamaca dan macopat, semua tulisannya ditulis menggunakan aksara Arab. Menariknya, teks arab tersebut hanya difungsikan sebagai aksara -huruf, tanda baca- saja, sedangkan bahasa yang digunakan masih menggunakan bahasa Jawa Kromo. Penggunaan aksara Arab bisa diartikan sebagai upaya men-genalkan budaya Arab kepada masyarakat.
Hal ini diperlukan karena untuk mempelajari Islam, mereka dituntut untuk membaca Al Quran dan beberapa kitab-kitab lainnya yang sebagian besar ditulis dengan aksara Arab. Dengan mengangkat narasi pandhâba sebagai me-dium cerita, semangat dan gairah masyarakat untuk membaca akan tergugah, dan setidaknya masyarakat akan terbiasa dengan aksara Arab tersebut.
Pertemuan budaya yang tertuang dalam teks mamaca tersebut menandakan bahwa peran Wali Sanga dalam hal syiar Islam cukup berhasil dan lebih bersifat negosiatif yakni dengan menego-siasikan, mempertemukan dan mengombinasikan kebudayaan Jawa-Hindu dengaų kebudayaan Arab-Islam tanpa mengubahnya secara keseluru-han.
Mamaca bisa dikatakan pengembangan macopat Jawa dalam versi Madura. Selain pertemuan unsur budaya Jawa dan Arab, mamaca turut mengandung unsur budaya Madura yang dominan. Mamaca dalam masyarakat Madura bentuknya kompleks karena ada unsur tafsir di dalamnya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa tradisi mamaca berasal dari Jawa.
Sebagian besar tokang maca dan juru ulas mamaca sebenarnya bukan berasal dari etnis Jawa. Mereka tidak biasa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jawa. Mereka menembangkan teks mamaca berbahasa Jawa dengan logat Madura yang kuat, terkadang juga mencampurnya dengan bahasa Madura, jika ada beberapa kosa kata yang tidak dipahami. Para juru ulas umumnya hanya menghafal kata kunci dan beberapa kosakata dalam bahasa Jawa saja, selebihnya mereka mengembangkan daya nalar dan tafsirnya masing-masing.
Pada titik inilah kita bisa melihat sisi kreativitas yang tinggi dari para pelaku mamaca Madura. Selain dibutuhkan kemampuan dalam membaca aksara arab, mereka harus menghafal beberapa kosa kata bahasa Jawa kromo beserta maknanya dan mengembangkan nalar dalam menafsirkan maknanya ke dalam bahasa Madura.
Di dalam menaf-sir mereka juga harus memahami konteks ceritanya, tokohnya, serta padanan kata yang sesuai berdasarkan konteksnya. Tidak hanya itu, ihwal yang justru paling penting dan utama adalah kemampuan estetisnya, yakni bagaimana para pelaku mamaca tersebut harus menguasai jenis-jenis tembhâng, teknik vokalnya, serta pen-jiwaan dalam melagukannya.
Tradisi mamaca dapat dikatakan sebagai produk kebudayaan hasil akulturasi budaya Jawa, Madura dan Arab, yang lahir dari proses internalisasi nilai-nilai Islam pada masyarakat Jawa dan Madura. Melalui tradisi mamaca kita bisa melihat peran syiar Islam (Wali Sanga) melalui kultur lokal.
Senjakala Tradisi Mamaca
Seperti halnya nasib seni tradisi pada umumnya, mamaca pada kondisi hari ini juga tinggal menanti waktu untuk benar-benar hilang digilas zaman. Mengapa demikian? Sejauh pengamatan penulis, hampir semua kelompok mamaca di Situbondo putus regenerasi, bahkan sudah banyak beberapa pelaku yang meninggal dunia tanpa meninggalkan pewaris atau penerusnya. Berdasarkan wawancara dengan para pelaku. setidaknya ada beberapa persoalan yang membuat kesenian ini mulai ditinggalkan yaitu;
1). Perkembangan media informasi dan teknologi yang cepat tanpa diimbangi pemahaman yang seimbang. Munculnya media televisi dan internet telah mengubah kebi-saan menonton masyarakat. Seni tradisi yang tadinya merupakan sebuah tontonan sekaligus tuntunan, kini telah tergeser keberadaannya dengan tayangan-tayangan alterna-sifatnya hanya sebatas hiburan dan pemuas hasrat sesaat.
Bentuk mamaca yang sederhana juga dinilai ketinggalan zaman atau terkesan tidak mengikuti perkembangan zaman. Menurut Sami’an, sejak maraknya televisi, orang-orang di desanya sudah tidak lagi ‘betah’ menonton dan mendengarkan mama-ca yang notabene memakan waktu lama dan membutuhkan perenungan mendalam. Mereka lebih memilih televisi untuk memuaskan keinginan emosionalnya.
2). Berkembangnya wacana pemurnian (puritanisme) Islam. Khusus di Situbondo sejak awal tahun 2000-an, wacana pemurnian Islam muncul dan sempat membuat trauma para pelaku mamaca. Berdasarkan penuturan Mattahir, pada saat itu ada ormas yang sengaja mengumpulkan para pelaku mamaca, mengklaim mereka dengan menyematkan isu ‘sesat’, dan memaksa mereka untuk menghentikan kegiatan mamaca karena dianggap telah sesat dan merusak aqidah Islam.
Imbas dari fenomena tersebut cukup terasa di lingkungan masyarakat Situbondo. Kini para pelaku mamaca cenderung berdiam diri dan tidak melayani undangan tanggapan kalau tidak karena terpaksa. Sebagian masyarakat juga memiliki pandangan bahwa mamaca bukanlah tradisi Islam ‘murni’ dan terkesan dibuat-buat ceritanya. Saat ini kegiatan ruwatan masyarakat Madura di Situbondo masih berlangsung hanya saja kegiatan mamaca-nya diganti dengan kegiatan khataman Al-Quran dan pengajian Yasin-an.
Beberapa pelaku mamaca mau tidak mau juga harus beradaptasi dengan kondisi masyarakat. Saat ini mereka juga melayani undangan ruwatan berupa khataman Al Quran dan pengajian Yasin-an.
3). Tingkat kerumitan (kesulitan) yang tinggi. Mamaca adalah seni tradisi yang membutuhkan kemampuan intelektual, kreativitas, emosional dan teknik/praktik keterampilan yang tinggi. Sulitnya membaca teks Arab berbahasa Jawa, menerjemahkannya ke dalam bahasa Madura dan menyanyikannya dalam bentuk tembhâng tertentu, membuat generasi muda enggan untuk mempelajari kesenian ini.
Belum lagi dengan bentuknya yang terkesan ‘monoton’, mereka harus rela berlama-lama duduk bersila sembari membaca teks mamaca hingga dini hari. Unsur cerita yang dibacakan juga kurang begitu dikenal bagi generasi muda saat ini. Perihal inilah yang membuat proses pewarisan seni tradisi mamaca tidak berjalan dengan baik. Perlu dicarikan metode serta pendekatan yang kreatif dan partisipatif supaya generasi muda mau mengenal, memahami dan melestarikan seni tradisi ini.
4). Kurangnya perhatian pemerintah. Dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh para pelaku mamaca, hal yang paling mem-perihatinkan ialah ketidakhadiran pemerintah. Pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung dan pelestari kebudayaan, termasuk di dalamnya seni tradisi, justru tidak memperhatikan nasib tradisi mamaca yang sedang sekarat ini. Yang banyak terjadi, khususnya di Situbondo, pemerintah cenderung mengikuti tren/gaya ‘perayaan kebudayaan’.
Memandang kebudayaan sebagai objek yang layak untuk dimeriah-kankan, difestivalkan dan dijual demi kepentingan pariwisata. Alih-alih memperhatikan nasib seni tradisi dan senimannya, mereka justru sibuk mengeksploitasi ke’unikan’ dan ke’eksotikan’ budayanya untuk dikomodifikasi dalam perayaan-per-ayaan budaya berwajah pariwisata. Di sisi lain para seniman tradisi harus bergelut dengan dinamika hidup yang semakin sulit dihadapi. Mereka dituntut untuk selalu mem-pu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang semikin hari semakin menyulitkan.
Tradisi mamaca merupakan warisan budaya Madura yang mengandung nilai-nilai kearifan dan keluhuran manusia. Sebagai produk budaya, ia menjadi penting untuk dilestarikan supaya nilai-nilai ke-luhurannya masih tetap hidup dalam masyarakat.
Melihat kondisi seni tradisi mamaca kini yang hampir mati, siapkah kita kehilangan akar budaya kita sendiri dan menggantinya dengan budaya televisi? Siapkah kita kehilangan identitas budaya lalu terseret arus budaya global yang ditunjang oleh internet? Atau mampu dan maukah kita menguatkan akar budaya kita sendiri sebagai-dasar dalam menghadapi perkembangan zaman?*
Daftar Pustaka
Bouvier, Hélèn. 2002. Lèbur!: Seni Musik dan Pertunjukan dalam Masyarakat Madura. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Rifa’i, Ahmad. 2017. Sepenggal Kearifan Bondowoso, Tradisi Mamaca Madura Parry – Lord’s Perspective, Yogyakarta: Diandra Kreatif.
Daftar Informan
Imam Kutunuk, Budayawan Situbondo
Hendrik, Pemain Suling (tokang solèng) mamaca di Besuki
Mattahir, Tukang Baca (tokang mamaca)
Sami’an, Tukang Baca (tokang mamaca) dan Juru Ulas (tokang tegghes)