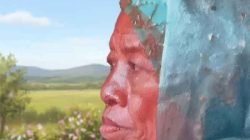Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan di Desa Bangkal, Kecamatan Kota Sumenep. Kabut tipis bergelayut di antara pepohonan kelapa dan suara ayam jantan bersahut dari kejauhan. Di tengah suasana yang teduh itu, terdengar lantunan tahlil dari arah sebuah kompleks tua yang dikelilingi pagar batu putih. Di sinilah masyarakat mengenalnya sebagai Asta Sunan Paddusan, tempat peristirahatan seorang tokoh besar yang hingga kini namanya terus disebut dalam doa orang-orang Madura.
Seorang lelaki tua bersarung kotak-kotak, yang setiap pagi menyapu halaman asta, menyapa pelan sambil mengangkat tangan ke dada. “Dari dulu tempat ini tak pernah sepi,” katanya. “Orang datang dari jauh, bukan sekadar ziarah, tapi nyareh berkah.” Ia lalu menunjuk ke arah sumur tua di sisi barat asta. “Dari sumur itulah semua cerita dimulai. Dari air, dari adudus, dari paddusan.”
Air, Asal-Usul, dan Nama yang Menjadi Doa
Nama Paddusan berasal dari kata pa’adusan dalam bahasa Madura, berarti “tempat mandi”. Bukan sembarang mandi, tetapi ritual pembersihan diri—lahir dan batin. Menurut tutur masyarakat setempat, dahulu di tempat inilah Raden Bindara Diwiryapada, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Paddusan, sering memandikan orang-orang yang baru masuk Islam. Setelah mereka mengucap dua kalimat syahadat, sang wali akan menuntun mereka menuju sumur di bawah rindangnya pohon beringin. Air dari sumur itu, kata orang, selalu terasa sejuk dan jernih meski kemarau panjang.
Dari situlah muncul nama “Paddusan”—tempat adudus para mualaf.
Sunan Paddusan bukan sekadar guru agama, ia adalah simbol penyucian diri. Di Madura, air bukan hanya sumber kehidupan, melainkan juga lambang kesucian dan keseimbangan. Air menghubungkan langit dan bumi, seperti ajaran para wali yang menghubungkan manusia dengan Tuhan tanpa meninggalkan akar budayanya.
Riwayat lisan menyebutkan bahwa Raden Bindara Diwiryapada masih memiliki pertalian darah dengan Sunan Ampel di Surabaya, salah satu Wali Songo. Ia dipercaya datang ke Sumenep sekitar abad ke-15, pada masa kerajaan lokal mulai mengenal ajaran Islam. Sebagai ulama muda yang penuh semangat, ia melihat Madura Timur sebagai tanah yang subur untuk menanam nilai-nilai baru tentang keimanan dan kebersamaan.
Ia tidak membangun pesantren besar seperti para penerusnya kelak. Dakwahnya dilakukan dari rumah ke rumah, dari ladang ke ladang, di sela-sela aktivitas masyarakat nelayan dan petani. Ia menyapa mereka dengan bahasa yang sederhana, menggunakan peribahasa lokal, menanamkan Islam melalui budaya yang sudah akrab.
Di Antara Sumur dan Sembilan Sumber Air
Selain sumur utama di dekat astanya, di sekitar kampung juga terdapat sembilan sumur yang diyakini dibuat oleh beliau untuk masyarakat. Desa di sebelah barat kemudian dikenal sebagai Parsanga, yang menurut kisah berasal dari kata paregi sasanga—sembilan sumur. Masyarakat percaya sumur-sumur itu memiliki tuah: airnya membawa kesejukan batin, dan setiap kali musim kemarau, sumur-sumur itu tetap mengalir.
Suatu kisah yang kerap diceritakan orang tua di Bangkal menyebutkan: ketika masyarakat dilanda kekeringan panjang, Sunan Paddusan menancapkan tongkatnya ke tanah sambil berdoa. Dari sana keluar mata air yang kemudian menjadi sumur pertama di Paddusan. “Tanah ini tidak kekurangan air karena doa Sunan,” kata Pak Samsuri, juru kunci asta. “Airnya tidak pernah habis, bahkan ketika sumur lain mengering.”
Namun yang menarik, Sunan Paddusan tidak pernah menganggap mukjizat sebagai miliknya. Ia selalu menekankan bahwa semua itu hanyalah pertanda kekuasaan Allah. Ia mengajarkan masyarakat untuk bersyukur dengan menjaga air, menjaga tanah, dan menjaga hubungan antar sesama. Nilai itu yang kemudian menjadi inti ajaran beliau: kebersihan hati, kesederhanaan hidup, dan ketaatan tanpa pamrih.
Dari Pesan Dakwah ke Budaya Lokal
Cara berdakwah Sunan Paddusan terbilang unik. Ia tidak memaksa masyarakat meninggalkan kepercayaan lama secara serta-merta, melainkan meresapinya perlahan. Tradisi padusan atau mandi bersama menjelang Ramadan, misalnya, merupakan bentuk adaptasi dari ajaran beliau. Ritual itu dahulu dimaksudkan sebagai penyucian sebelum menyambut bulan suci. Di Madura, tradisi ini masih bertahan—sebuah jembatan antara Islam dan kebudayaan lokal.
Ia juga dikenal sebagai penggerak sosial. Konon, beliau membangun jaringan sumur dan saluran air untuk mengairi sawah-sawah di sekitar Bangkal. Beberapa sumur tua dengan batu kapur besar di bibirnya masih tersisa hingga kini, dijaga seperti pusaka. “Sunan Paddusan tidak hanya mengajarkan shalat dan puasa,” tutur salah satu tokoh masyarakat setempat, “beliau mengajarkan bagaimana hidup dengan berguna.”
Legenda tentang kebaikannya tak terhitung jumlahnya. Dikisahkan, suatu ketika seorang ibu datang menangis karena anaknya sakit keras. Sunan Paddusan menenangkan sang ibu, lalu mengambil air dari sumur Paddusan dan memercikkannya pada anak itu. Tak lama kemudian anak itu sembuh. “Bukan airnya yang menyembuhkan,” kata beliau, “tetapi kasih yang kita titipkan lewat doa.”
Di Antara Mistik dan Kenyataan
Sebagai tokoh sufi, Sunan Paddusan dikenal memiliki kedalaman spiritual yang luar biasa. Dalam tradisi Madura, para wali sering disebut pariyah angghuyur bherkat—orang yang menebarkan berkah. Tidak sedikit cerita karomah yang beredar, dari kemampuan beliau membaca hati orang, hingga kisah bahwa jasadnya tetap utuh bertahun-tahun setelah wafat. Namun bagi masyarakat Bangkal, yang lebih penting bukanlah keajaiban, melainkan keteladanan.
Makam Sunan Paddusan kini menjadi tempat ziarah. Di bulan Maulid dan Ramadan, ratusan peziarah datang membawa bunga, air, dan doa. Mereka duduk berdiam di bawah pohon asri, membaca manâqib dan barzanji. Di malam tertentu, terlihat sinar lampu minyak berkelip di antara nisan-nisan tua. Suara gamelan saronen dari kejauhan seperti mengiringi suasana khidmat itu.
Masyarakat percaya, ziarah ke asta bukan sekadar meminta berkah, tapi mengenang perjuangan leluhur yang menanamkan nilai. Sebab di Madura, nyareh berkat bukan berarti mengharap sesuatu secara duniawi, melainkan mengingat kembali siapa diri kita di hadapan Tuhan dan leluhur. Sunan Paddusan adalah cermin dari kesadaran itu.
Warisan yang Hidup di Pesisir Timur
Di sekitar lokasi asta, kini berdiri pesantren-pesantren kecil yang didirikan oleh keturunan murid-murid beliau. Salah satunya dikenal dengan nama Pesantren Al-Paddusan, tempat para santri belajar tafsir dan fikih sekaligus menjaga tradisi lokal. Setiap tahun, menjelang bulan Rabiul Awal, mereka menggelar nyadar sumber—sebuah upacara membersihkan sumur tua dengan doa dan lantunan sholawat.
Bagi warga Sumenep, ajaran Sunan Paddusan masih relevan: bahwa agama harus menyejukkan, bukan menghakimi; menghidupkan, bukan menakut-nakuti. Bahkan beberapa istilah dalam masyarakat seperti andhus ka Paddusan (mandi ke Paddusan) kini bukan hanya bermakna fisik, tetapi juga spiritual: membersihkan hati sebelum menghadapi sesuatu yang besar.
Tak sedikit pula peneliti budaya yang datang menelusuri jejak beliau. Ada yang menulis disertasi tentang relasi Islam dan air di Madura, ada pula yang meneliti bagaimana toponimi lokal terbentuk dari kisah-kisah dakwah seperti ini. Dari hasil wawancara dan catatan lokal, terlihat bahwa nama-nama seperti Paddusan, Parsanga, hingga Bangkal bukanlah sekadar wilayah, melainkan bab dari narasi besar Islamisasi Madura.
Cermin dari Kelembutan Dakwah
Ketika Islam datang ke Madura, sebagian wilayah telah mengenal sistem kerajaan dan kepercayaan animisme-Hindu. Sunan Paddusan memilih jalan tengah: ia tidak menentang, tapi mengislamkan simbol-simbol lama dengan makna baru. Air yang dulu dianggap sakral, kini menjadi media thaharah (penyucian). Upacara yang dahulu bersifat magis, diubah menjadi syukur kepada Allah. Dalam pendekatan seperti itulah Islam menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan sesuatu yang dipaksakan.
Sikap ini menjelaskan mengapa masyarakat Madura memandang para wali bukan hanya sebagai tokoh agama, tetapi juga leluhur yang memelihara keseimbangan alam dan sosial. Dalam kisah-kisah yang dituturkan di beranda rumah atau di langgar-langgar kecil, nama Sunan Paddusan sering disebut bersama nama-nama besar lain seperti Sunan Kudus atau Sunan Ampel, meski dalam skala lokal.
Bagi mereka, Sunan Paddusan adalah lambang kesabaran dan keikhlasan. Ia tidak menulis kitab, tidak mendirikan kerajaan, tetapi meninggalkan sumur—sumber kehidupan yang terus mengalir. Air dari sumur itu, dalam pandangan masyarakat, seolah tak pernah berhenti menjadi rahmat bagi tanah yang panas dan tandus.
Menyapa Leluhur di Tengah Zaman Modern
Kini, jalan menuju Asta Sunan Paddusan sudah diaspal. Di kanan-kirinya, pedagang menjual bunga, dupa, dan air botolan yang diambil dari sumur tua. Anak-anak muda kadang datang hanya untuk berswafoto, tapi tak jarang mereka ikut menundukkan kepala saat orang-orang membaca tahlil. Modernitas mungkin telah mengubah cara berziarah, namun esensi spiritualnya tetap terasa.
Bagi masyarakat Madura, ziarah ke asta bukan sekadar kegiatan religius, melainkan juga pernyataan identitas. Mereka datang untuk “mengenali asal” — mengikat kembali tali dengan tanah dan air leluhur. Ketika tangan mereka menyentuh batu nisan Sunan Paddusan, mereka seperti menyentuh sejarah panjang tentang bagaimana Islam tumbuh dengan lembut di tanah garam ini.
Suara azan dari langgar di ujung jalan terdengar sayup. Angin laut membawa aroma asin yang samar, bercampur wangi bunga kenanga. Di halaman asta, seorang ibu muda menimba air dari sumur, mencuci tangannya, lalu memercikkannya ke wajah. Ia tersenyum kecil, lalu berdoa dalam hati. “Moga-moga sejuk seperti air Sunan,” katanya pelan.
Begitulah, di ujung timur Madura, legenda Sunan Paddusan bukan sekadar kisah lama. Ia hidup di udara, di air, di setiap langkah masyarakat yang percaya bahwa kesucian bukan hanya tentang ibadah, tapi tentang bagaimana hati tetap jernih dalam menghadapi hidup. Seperti air yang tak pernah menolak siapa pun yang datang, begitu pula ajaran beliau: mengalir, menenangkan, dan memberi kehidupan.
Sunan Paddusan bukan hanya nama yang tercatat dalam sejarah lokal Sumenep. Ia adalah simbol dari perjalanan panjang Islam yang berpadu dengan budaya. Dari air yang mengalir, lahir kearifan yang menyejukkan. Di tengah arus zaman yang serba cepat, kisahnya mengingatkan bahwa kemurnian hidup bisa dimulai dari kesederhanaan: dari setetes air, dari keikhlasan seorang manusia yang menyebarkan kebaikan tanpa pamrih.
(Lontar Madura, dihimpun dari beberapa sumber)